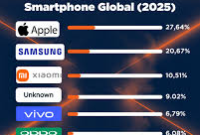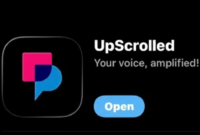Webhostdiy –– Pernahkah kita menyadari bahwa digitalisasi di Indonesia sering kali dirayakan melalui statistik dan dashboard? Padahal, di balik angka-angka itu, ada krisis yang terus bergulir—dan semua tentang manusia.
Mari kita simak kisah Bu Warti, seorang janda berusia 64 tahun dari desa dataran tinggi Wonosobo. Suatu hari, ia terpaksa pulang dari puskesmas karena tidak bisa membuka QR Code vaksin di ponselnya. Ponselnya hanya bisa SMS, sementara petugas kesehatan kebingungan karena sistem mewajibkan input melalui aplikasi. “Padahal saya sudah vaksin tiga kali,” ujarnya, suaranya penuh kebingungan dan kelelahan.
Tak jauh berbeda, seorang bidan di desa terpencil Maluku mengeluh karena laporan COVID-19 harus dikirim harian ke server pusat. “Kalau sinyal hilang, saya catat di kertas dulu, baru input seminggu sekali saat ke kota,” ceritanya. Akurasi data—bahkan nyawa—menjadi taruhan. Kisah-kisah ini membuktikan bahwa teknologi belum benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Infrastruktur yang Tak Merata: Masih Banyak yang Tertinggal
Faktanya, 13% desa di Indonesia masih belum terhubung internet. Desa-desa ini berada di wilayah terpencil dengan geografi sulit, termasuk di sektor kesehatan (Digitalmama.id, 2024). Di Aceh saja, 536 dari 6.497 desa tidak memiliki akses internet. Dari jumlah itu, 387 desa hanya terjangkau sinyal 2G—tidak cukup untuk internet—sementara 149 desa lainnya benar-benar blankspot (Cnnindonesia.com, 2022).
Bayangkan jika krisis terjadi di sana—gempa bumi atau lonjakan COVID-19 seperti Omicron 2022. Ketika aplikasi pelaporan tak bisa dipakai karena tidak ada sinyal, siapa yang bertanggung jawab? Apakah ini sekadar kebetulan, atau bukti bahwa digitalisasi Indonesia terlalu terpusat dan mengabaikan daerah pinggiran?
Kita tak bisa terus menyalahkan “akses internet” sebagai penyebab gagalnya pelaporan data. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga politik distribusi teknologi.
Tantangan di Perkotaan: Pengawasan Digital yang Mengkhawatirkan
Masyarakat perkotaan pun tak luput dari masalah serupa. Banyak negara mengalami “normalisasi pengawasan digital”, di mana pelacakan kontak dan pemantauan lokasi menjadi hal biasa—terutama saat darurat. Apakah Indonesia juga mengalaminya?
Studi ELSAM (2021) mengungkap bahwa data pengguna aplikasi pelacakan COVID-19 disimpan tanpa batas waktu jelas dan dipakai untuk keperluan lain tanpa pemberitahuan. Dua aplikasi pemerintah, PeduliLindungi (Kominfo) dan e-HAC (Kemenkes), dituding melanggar prinsip perlindungan data. Keduanya mengumpulkan data berlebihan—seperti lokasi real-time dan NIK—padahal seharusnya hanya butuh nama dan nomor telepon untuk pelacakan kontak.
PeduliLindungi juga dikritik karena menyimpan data secara sentral di server PT Telkom tanpa batasan akses jelas, berisiko bocor. ELSAM menuntut transparansi lebih besar, termasuk penjelasan perbedaan fungsi kedua aplikasi itu dan perlunya kebijakan privasi yang ketat.
Kapitalisme Digital: Siapa Pemilik Data Kita?
Euforia transformasi digital juga memunculkan pertanyaan kritis: siapa yang mengendalikan sistem ini? PeduliLindungi dikembangkan lewat kerja sama pemerintah-swasta. Tapi setelah pandemi mereda, ke mana data ratusan juta pengguna itu pergi?
Di sinilah kapitalisme digital mengintai. Ketika data menjadi komoditas, setiap krisis—termasuk kesehatan—bisa berubah jadi ladang bisnis bagi korporasi, tanpa persetujuan pemilik data.
Bekal ke Depan: Empat Solusi Mendesak
Agar digitalisasi benar-benar bermanfaat, kita perlu membangun sistem yang berfokus pada empat hal:
- Desentralisasi Akses
- Transparansi Data – Perlu ada dewan etika data yang mengawasi penggunaannya.
- Perlindungan Privasi – Kebijakan privasi harus jelas, termasuk batas waktu penyimpanan data dan larangan penggunaan di luar tujuan awal.
- Partisipasi Publik –
Kesimpulan: Digitalisasi Harus Manusiawi
Krisis di Indonesia—khususnya di bidang teknologi—memperlihatkan ketimpangan struktural, tarik-menarik kepentingan politik, dan ancaman kapitalisme data. Digitalisasi seharusnya memudahkan hidup, bukan malah meminggirkan mereka yang paling rentan.